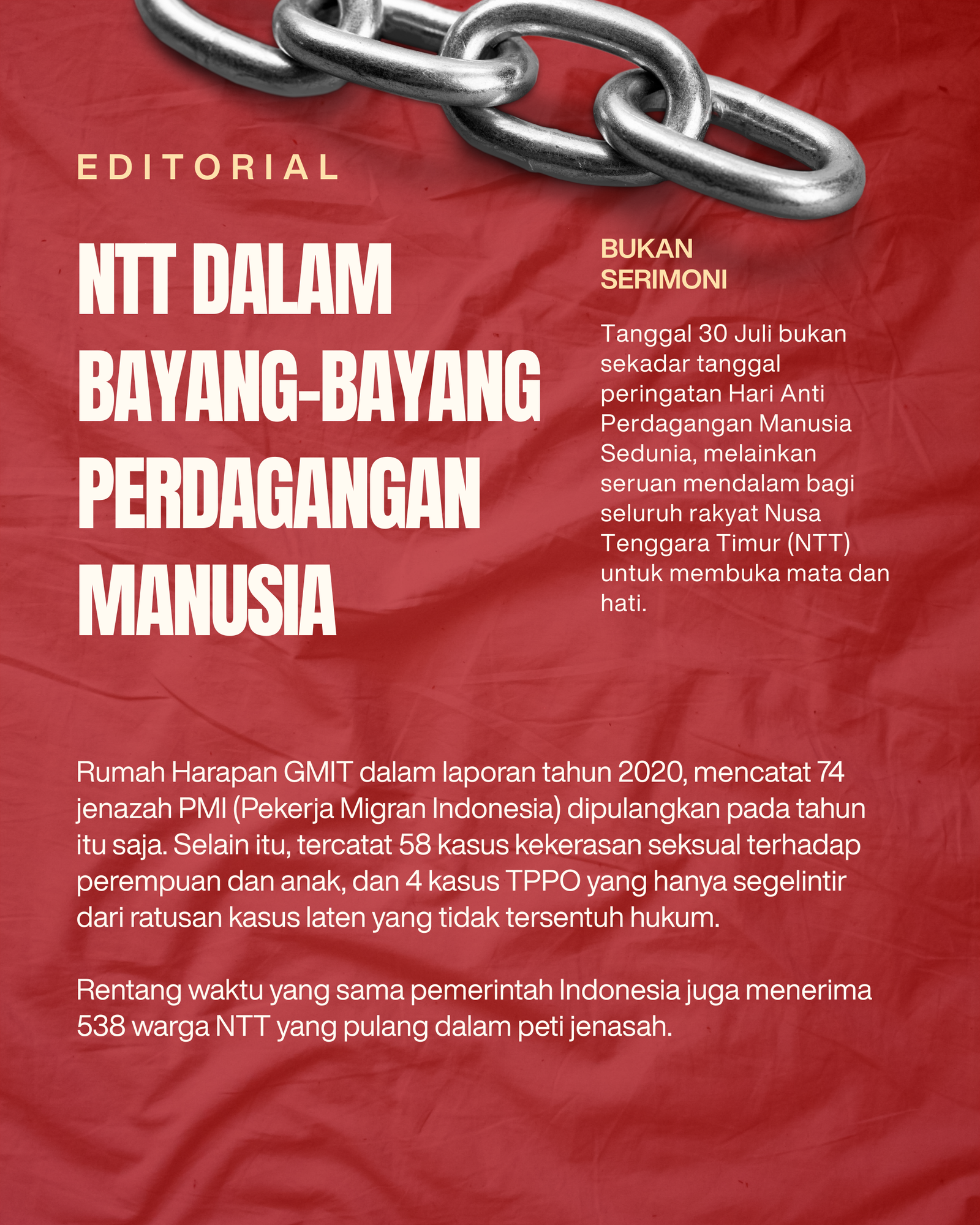Pandurakyat.id – Tanggal 30 Juli bukan sekadar tanggal peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia, melainkan seruan mendalam bagi seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membuka mata dan hati. Hari ini menjadi alarm kebangsaan yang telah lama dibungkam, menggema sebagai suara jeritan para korban yang terbenam di balik angka statistik yang dingin.
Dari kepala desa hingga Gubernur NTT, bahkan hingga ke lembaga negara pusat, ada kelumpuhan kolektif yang tak bisa lagi dibiarkan — mereka yang seharusnya melindungi dan memimpin justru hanya menjadi penonton bisu di tengah ribuan nyawa yang melayang.
NTT bukan dilihat sebagai sumber daya manusia yang unggul, melainkan telah meregang oleh reputasi pahit sebagai ladang subur perdagangan manusia. Fakta mengerikan ini terungkap nyata sejak awal 2024, sebanyak 124 jenazah pekerja migran ilegal dari NTT dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia.
Catatan Penting
Dalam tiga bulan pertama 2025, 24 peti mati lainnya tiba kembali, pembawa kabar duka yang mencerminkan tragedi berkepanjangan. Mereka tidak kembali sebagai pahlawan devisa, tapi sebagai korban dari negara yang gagal hadir dan melindungi warganya.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik; mereka adalah nyawa, keluarga yang hancur, dan luka bangsa yang menganga, hal ini diungkap secara tegas oleh anggota DPR RI, Rudi Kabunang, dalam sidang resmi parlemen dikutip dari laman Kompas.id.
Tapi tidak berhenti di angka. Dalam laporan Tempo.co, 10 Juni 2023, Komnas HAM menegaskan bahwa NTT kini berada dalam status darurat TPPO, dengan perekrutan dilakukan secara terbuka bahkan dengan dukungan dan restu dari aparat desa dan oknum pejabat imigrasi. Hal ini bukan lagi sekadar pembiaran, ini bentuk keterlibatan struktural yang disengaja.
Sementara itu, BBC Indonesia menelusuri lebih dalam jaringan calo di Sumba, TTS, dan Rote secara sistematis menjual anak-anak perempuan dengan iming-iming kerja di Malaysia, Batam, dan Singapura.
Para orang tua hanya menerima uang “sirih pinang” sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000, sementara mafia menerima Rp30–50 juta per kepala dari pengguna jasa di luar negeri. Apa ini bukan bentuk paling hina dari penjajahan antarmanusia?
Namun, di tengah kejahatan masif ini justru suara yang berseru dibungkam. Dilansir dari laman floresia.co seorang pastor Katolik juga aktivis kemanusiaan, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus, membongkar dugaan keterlibatan pejabat tinggi negara dan mengungkap jalur panjang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di NTT, ia bukan diberi ruang atau perlindungan hukum, melainkan dilaporkan ke polisi.
Ini bukan hanya kriminalisasi terhadap pembela HAM, tapi konfirmasi nyata bahwa sistem birokrasi dan bahkan lembaga agama lebih takut pada reputasi daripada kebenaran.
Pemerintah provinsi NTT, dengan seluruh aparaturnya, tidak hanya gagal memberikan perlindungan. Mereka adalah bagian dari masalah. Mereka menyaksikan ratusan nyawa anak bangsa dikirim keluar negeri seperti barang, diperkosa, diperbudak, tak dibayar, dan akhirnya dipulangkan sebagai tubuh kaku dalam peti plastik dan tetap memilih diam.
Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus mewakili keberanian yang langka dan sangat dibutuhkan dalam menghadapi kejahatan sistemik. Kendati keberanian untuk berbicara kebenaran tidak selalu berbuah perlindungan, malah sering berhadapan dengan ancaman hukum yang menjadi alat pembungkaman efektif.
Polda NTT, dalam satu dari sedikit langkah konkret, mengungkap 8 kasus TPPO dan 2 kasus penyelundupan manusia sepanjang akhir 2024 hingga Juni 2025. 13 tersangka ditangkap, banyak di antaranya hendak mengirim korban ke Malaysia dan Taiwan.
Tapi sayangnya, hingga kini tidak pernah ada audit menyeluruh terhadap dinas-dinas pemerintah daerah dan jalur administrasi yang jelas-jelas ikut memfasilitasi praktik ini .
Sebelumnya Rumah Harapan GMIT dalam laporan tahun 2020, mencatat 74 jenazah PMI (Pekerja Migran Indonesia) dipulangkan pada tahun itu saja. Selain itu, tercatat 58 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan 4 kasus TPPO yang hanya segelintir dari ratusan kasus laten yang tidak tersentuh hukum. Laporan ini membuktikan bahwa ini bukan situasi baru.
Selain itu melansir laman voaindonesia.com, dalam rentang waktu yang sama pemerintah Indonesia juga menerima 538 warga NTT yang pulang dalam peti jenasah. Mereka adalah para pekerja migran Indonesia yang terindikasi sebagai korban perdagangan manusia karena mayoritas PMI itu tidak memiliki surat — surat yang resmi.
Data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT mencatat pada tahun 2022 terdapat 106 PMI yang meninggal dunia, pada 2021, ada 121 PMI pulang sebagai jenazah, sementara pada 2020 ada 87 orang, 2019 ada 119 orang dan 2018 ada 105 orang.
Ini adalah kejahatan yang terus berlangsung karena negara memilih tidak hadir.
Lalu kepada siapa rakyat berharap? Jika Gubernur, para Bupati, DPRD, dan kepala dinas hanya duduk manis dalam kantor ber-AC sambil menggelar seremoni Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus, maka jelas mereka tidak lebih dari pemangsa bangsanya sendiri.
Di depan baliho “Stop Perdagangan Orang” mereka tersenyum, sementara di balik layar, anak-anak perempuan dari TTS dikirim seperti sapi ke luar negeri.
Sudah cukup bicara soal program kerja, angka statistik, dan janji kosong. Ini soal nyawa—nyawa anak-anak, saudara, dan warga Nusa Tenggara Timur yang direnggut oleh praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merajalela dan sistem yang telah gagal total.
Apa yang Perlu dilakuakan?
Pertama, pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan TPPO di NTT, karena pemerintah provinsi telah menunjukkan kegagalan yang tak terbantahkan. Ini bukan tindakan sewenang-wenang tetapi panggilan untuk menyelamatkan jiwa dan menghentikan tragedi yang terus berulang.
Audit menyeluruh terhadap institusi yang seharusnya melindungi rakyat—dinas tenaga kerja, aparat desa, imigrasi, dan seluruh rantai birokrasi yang telah terlibat atau menutup mata selama ini. Bubarkan semua yang terindikasi menjadi bagian dari kejahatan kemanusiaan ini.
Kedua, Segerah bentuk Komisi Independen Khusus, yang diawasi ketat oleh masyarakat sipil, gereja, Komnas HAM, dan lembaga internasional, agar transparansi dan keadilan terwujud tanpa kompromi.
Ketiga, kepastian hukuman maksimal, bahkan hukuman mati bagi para mafia dan aparat yang berkhianat melindungi jaringan kejahatan perdagangan manusia. Jangan biarkan satu nyawa lagi terenggut tanpa ada pertanggungjawaban berat.
Ini penting untuk membangun sistem keadilan yang nyata dan tidak bisa ditawar. Jangan pernah menunggu datangnya 17 Agustus untuk pidato merdeka, ketika kenyataannya 30 Juli berlalu dengan luka yang dibiarkan meradang tanpa tindakan.
Selama masih ada satu anak Nusa Tenggara Timur yang dijual oleh tangan birokrasi dan selama kekuasaan memilih diam dan acuh, maka Indonesia sejatinya belum merdeka.
Editor: Redaksi