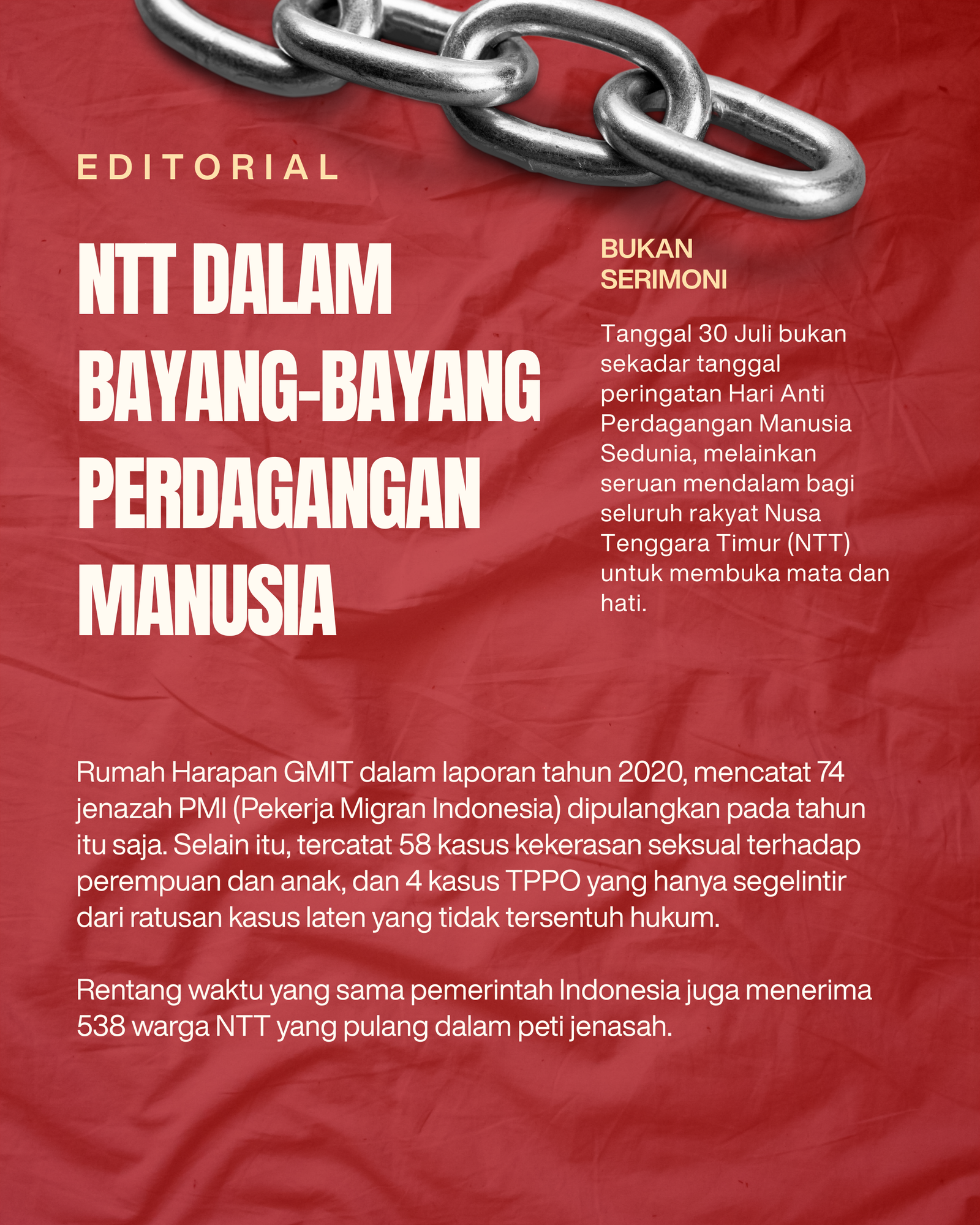Di balik jejak langkah kecil seorang gadis dari Pulau Rote – Nusa Tenggara Timur, ada sebuah kisah yang merobek sunyi dan mengguncang diam. Margaret, anak seorang kuli dengan rumah kayu yang rapuh, menapaki jalan yang sunyi dan pahit.
Rumah sederhana, ekonomi yang terbatas, bukan sekadar kata, namun medan pertempuran yang menguji kepercayaan dan keyakinannya.
Ketika ia menatap langit mimpi—Universitas Indonesia, pintu gerbang masa depan yang gemilang—bukannya petuah dan semangat yang datang, melainkan derasnya hujan kata-kata yang bisa meluluhkan hati.
Gurauan tajam dan cercaan membalut setiap sudut harapan yang ia genggam. “Gak bisa bayar uang sekolah tapi mau kuliah di UI,” bisik tetangga, seolah menggenggam palu hakim yang menghukum tanpa ampun.
“Miskin jangan kuliah!” bukan sekadar kalimat, tapi racun yang merayap perlahan, menancapkan duri di relung jiwa.
Kata-kata itu bukan hanya melemahkan, tapi mengancam untuk memadamkan api dalam dirinya. Namun Margaret, dengan keberanian yang diam-diam membara, menolak tunduk oleh gelap kata-kata itu.
Ia tahu, kemiskinan tidak boleh menjadi penjara bagi mimpi. Dalam setiap hinaan yang menderu, ada kekuatan tak terlihat yang tumbuh, membentuk tekadnya menjadi baja. Ia bukan hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi untuk jutaan jiwa yang terpinggirkan dan diragukan.
Datangnya Pak AG Sudibyo, sang dosen legendaris, seperti embun pagi yang menyapa rimbunan harapan yang hampir pudar. Sebuah pengakuan bahwa perjuangannya bukan hanya nyata, tapi juga layak mendapatkan penghormatan. Sosok yang memberi makna baru bahwa batasan sosial tidak boleh menentukan nasib seseorang.
Racun Normalisasi Anggapan Remeh pada Mental
Dalam ruang sunyi jiwa yang terpenjara kata-kata, ada racun yang merayap tanpa suara — sebuah racun bernama normalisasi hinaan dan anggapan remeh. Bukan sekadar bisikan, melainkan mantra tak kasat mata yang menanamkan singgasana keraguan dalam hati.
Bayangkan bagaimana benih kecil ketidakpercayaan itu tumbuh subur, merangsek ke sudut-sudut terdalam, membentuk benteng tipis yang rapuh, namun kuat menghalangi sinar harapan.
Dalam kegelapan psikologis itu, banyak jiwa jatuh ke dalam pusaran self-fulfilling prophecy—ramalan yang terpenuhi oleh keyakinan sendiri. Mereka yang terus-menerus didoktrin dengan kata “tidak mampu” lambat laun mulai percaya, menyerah, dan membiarkan mimpi mereka musnah dalam diam. Sebuah stigma sosial yang mengkotakkan mereka dalam kelas-kelas yang dibuat oleh stereotip, menjadikan potensi sebagai barang mahal yang tak bisa dimiliki semua orang.
Margaret, gadis kecil dari Pulau Rote nyaris terhanyut dalam pusaran itu. Di ambang menyerah, saat gelap pikiran membayangi, suara-suara dalam dirinya berbisik pelan, “Apakah aku memang tidak bisa?” Namun, di saat itulah kekuatan luar biasa bangkit, seperti cahaya redup yang perlahan menyulut bara dalam dadanya.
Menjelang penutupan pendaftaran SNBP, tekadnya menguat, bukan hanya dari dalam dirinya, tapi juga dari percikan harapan yang datang dari dalam dan luar. Sebuah bukti nyata bahwa dukungan, sekecil apa pun, mampu memutus lingkaran kelabu itu dan menata ulang hati untuk melangkah kembali ke medan juang.
Inilah cerita tentang jiwa yang berani menolak untuk terbelenggu oleh stigma, tentang hati yang menolak takdir ditulis oleh cercaan, dan tentang mimpi yang menolak padam meski disiram kerapuhan keyakinan.
Kisah ini memanggil kita semua untuk merenungi betapa pentingnya menghentikan racun normalisasi anggapan remeh, demi melahirkan generasi yang percaya diri, kuat, dan tak gentar melangkah melewati badai kehidupan.
Melampaui Stigma dan Membangun Ketahanan Mental
Ketika cibiran dan keraguan menjadi suara dominan, anak muda yang kurang beruntung secara ekonomi harus mengembangkan ketahanan mental yang kuat agar tidak terpuruk. Dalam psikologi, ini disebut sebagai resilience (ketangguhan psikologis) — kemampuan adaptif menghadapi tekanan negatif dengan tetap menjaga kesehatan mental dan semangat juang.
Kisah Margaret mengilustrasikan bagaimana ketahanan ini dapat dipupuk, dan bagaimana menyediakan akses terhadap dukungan moral, beasiswa, dan fasilitas pendidikan dapat menjadi kunci pembuka jalan keberhasilan.
Lebih jauh, kisah ini juga menyerukan kepada masyarakat agar memutus siklus penormalan stigma negatif yang selama ini membatasi mimpi anak-anak dari latar belakang kurang mampu. Pendidikan inklusif dan persepsi positif perlu dibangun sebagai landasan sosial agar tidak ada lagi penilaian yang mematikan seperti “miskin jangan kuliah”.
Kisah Margaret bukan hanya cerita keberhasilan individu, melainkan juga panggilan untuk pergeseran paradigma sosial yang selama ini tanpa sadar mengekang potensi generasi muda. Dengan mengakhiri normalisasi anggapan remeh dan memberikan dukungan nyata, kita dapat membantu mewujudkan mimpi yang lebih besar dan menciptakan perubahan sosial yang lebih baik.
Editor: Nasruddin