Oleh: Melcy Making
***
Cerita Licia Ronzulli, adalah anggota Parlemen Eropa asal Italia. Baru-baru ini menarik perhatian dunia karena selalu membawa serta putrinya ke ruang sidang parlemen. Selama bertahun-tahun, Licia hadir bersama sang anak, menunjukkan simbol penolakan atas pilihan “jadi ibu atau wanita karier.”
Dari awalnya digendong dalam kain gendongan, hingga sang putri mulai beranjak besar, Licia tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Bisa dibilang, sang anak “tumbuh besar” di dalam ruang parlemen, menjadi saksi hidup atas semangat ibunya.
Di sebuah aula megah Parlemen Eropa, ia menapaki panggung politik sambil menyusui bayi berusia 44 hari yang terbungkus dalam selendang putih. Licia Ronzulli bukan sekadar mengumumkan kebijakan; ia memperlihatkan aksi nyata bahwa peran keibuan tidak menghalangi ambisi politik.
Di sisi lain, dalam karya fiksi “Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan”, berceita tentang seorang politikus perempuan bernama Suad, berambisi tinggi yang mengorbankan identitasnya sebagai wanita demi karier, hingga terjerat dalam kekosongan emosional dan kegagalan pribadi.
Kedua narasi ini berdiri sebagai antitesa yang saling melengkapi: satu mencontohkan integrasi peran, yang lainnya memperingatkan konsekuensi bila peran tersebut dipisahkan.
Cerita Licia Ronzulli: Gestur Keibuan yang Melampaui Stereotip


Sejak usia 7 minggu ia menjemput bayinya berusia 44 hari dalam selendang ke dalam aula Strasbourg, menegaskan bahwa menjadi ibu bukanlah pilihan yang harus mengorbankan karier politik.
Ini bukan sekadar aksi simbolik, langkah Ronzulli adalah gestur keibuan yang menuntut perubahan struktural. Ia berkata, “Itu bukan gestur politik; pertama‑tama, itu gestur keibuan . Bahwa saya ingin sebisa mungkin bersama putri saya, dan mengingatkan orang‑orang bahwa ada perempuan yang tidak memiliki kesempatan ini.”
Kata‑kata itu menggemakan suara jutaan ibu yang berjuang menyeimbangkan tanggung jawab domestik dengan ambisi professional.
Setiap kali Ronzulli mengangkat mikrofon, di sampingnya ada sosok kecil yang mengamati—sebuah gambar kuat tentang work‑life balance yang nyata. Selama tiga tahun, Vittoria “tumbuh besar” di dalam bangunan institusi tinggi, menyaksikan ibunya berdiskusi kebijakan, menandatangani resolusi, bahkan ikut serta dalam sesi voting.
Mari kita melihat kisah ini sebagi pengaruh simbolik pada persepsi publik dan dampaknya pada kebijakan.
Pertama, Ronzulli telah memperlihatkan bahwa kebijakan kerja yang inklusif bukan sekadar ideal, melainkan kebutuhan nyata. Dengan menampilkan Vittoria di panggung politik, ia menginspirasi ibu‑ibu di seluruh dunia untuk menuntut hak yang sama, hak untuk bekerja tanpa meninggalkan anak, sekaligus hak anak untuk melihat peran ibu mereka secara publik.
Kisahnya kini menjadi bahan bakar bagi gerakan global yang menuntut tempat kerja ramah keluarga, sekaligus menegaskan bahwa kekuatan perempuan terletak pada kemampuan mereka menggabungkan peran—bukan memilih salah satunya.
Penelitian menunjukkan bahwa representasi visual perempuan dalam posisi kepemimpinan meningkatkan kepercayaan diri perempuan di tempat kerja sebesar 23 % (World Economic Forum, 2023).
“Jika seorang ibu dapat berdiri di antara para legislator sambil merawat bayinya, maka semua perempuan berhak memiliki ruang yang sama.”
Kedua, Banyak perempuan menghadapi tekanan untuk memilih satu peran saja, tapi Ronzulli membuktikan bahwa dua peran bisa berjalan bersamaan jika support system yang baik dari sekitar. Menghapus stigma “pilih karier atau jadi ibu” bukan sekadar slogan; ia menuntut komitmen kebijakan, infrastruktur, dan perubahan mentalitas yang dimulai dari contoh‑contoh berani seperti Licia Ronzulli.
Mari menolak narasi mengekang ini dan membangun lingkungan kerja yang menghargai peran ganda Perempuan, karena ketika wanita tidak dipaksa memilih, seluruh masyarakat akan maju.
Ketiga, dari Licia Ronzulli perempuan bisa belajar bahwa perempuan bisa produktif secara profesional tanpa harus meninggalkan perannya sebagai ibu. Aksinya yang membawa bayi ke Parlemen Eropa menjadi pionir perubahan kebijakan yang lebih ramah keluarga.
Bagi banyak ibu pekerja di dunia, aksinya ini memberi harapan dan kekuatan bahwa kesuksesan karier dan kehidupan keluarga bisa diperjuangkan bersamaan. Bukan hanya milik orang lain, tapi juga hak semua perempuan.
Kisah Saud dan Ambisi Tanpa Penopang
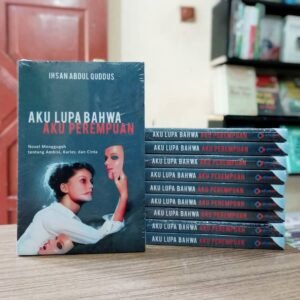
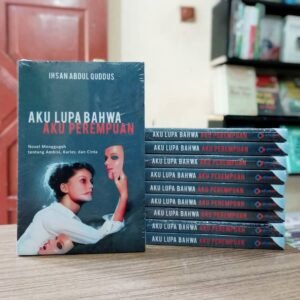
Berbeda dengan itu sebuah Novel karya Ihsan Abdul Quddus bercerita tentang kisah seorang perempuan yang memiliki ambisi sangat besar. Karena ambisi itu pula ia bahkan lupa bahwa sejatinya ia adalah seorang perempuan.
Bagaimana tidak. Saud (Tokoh Utama) mengorbankan segalanya. Cinta dan keluarganya telah ia kesampingkan demi sebuah ambisi menjadi seseorang yang selalu menjadi bintang dimanapun tempatnya.
Ia telah menjadi seorang politisi perempuan, kiprahnya di parlemen dan berbagai organisasi pergerakan terbilang sukses hingga menempatkan dirinya dalam lingkaran elite kekuasaan. Dibalut dengan latar belakang politik yang masih konservatif, telah menempatkan dirinya sebagai fenomena baru dalam kesetaraan gender.
Namun, pencapaian itu bukanlah akhir. Ia selalu ingin mempertahankan posisi menjadi bintang tokoh tersebut.
Usahanya menggapai ambisi tersebut telah mengantarkannya pada sebuah kehampaan yang menyelimuti kehidupan pribadinya. Masalah demi masalah selalu datang silih berganti. Pernikahannya selalu gagal.
Bahkan anak semata wayang yang ia anggap sebagai harta paling berharga justru lebih akrab dengan sang ibu tiri. Kebahagiaannya seolah dibuat-buat untuk menutupi kesepian yang mendera.
Kendatipun demikian, Novel ini berfungsi sebagai cermin kritis yang menyoroti bahaya “self‑sacrificing ambition” di mana perempuan dipaksa memilih antara karier atau keibuan, tanpa adanya kerangka kebijakan yang inklusif.
Kisah Licia Ronzulli membuktikan bahwa aksi simbolik dapat menjadi katalis perubahan struktural, menegaskan hak ibu untuk bekerja tanpa mengorbankan kehadiran fisik pada anak. Sebaliknya, novel “Aku lupa bahwa aku perempuan” memperingatkan bahwa ambisi yang terputus dari dukungan sosial berujung pada kehampaan pribadi.
Kedua narasi, meski berposisi antitesa tetapi saling menginspirasi: satu memberikan contoh integrasi, yang lain memberikan peringatan kebutuhan akan kebijakan.
Jika kita menginternalisasi pelajaran ini, kemukinan kita tahu pentingnya menyediakan infrastruktur yang mendukung, menormalisasi peran ganda, dan menyuarakan kisah nyata serta fiksi—maka perempuan tidak lagi harus memilih, melainkan menjadi agen perubahan yang menggerakkan seluruh masyarakat ke arah yang lebih adil dan produktif.
Lalu apa yang perlu dilakukan?
Pertama, Pentingnya Kebijakan Kerja Fleksibel. Dengan implementasikan cuti melahirkan berbayar minimal 6 bulan, ruang menyusui, dan opsi kerja remote di lembaga publik maupun swasta.
Kedua, Program Mentoring dengan membangun jaringan mentor perempuan senior yang telah berhasil menggabungkan peran, mirip contoh Ronzulli, untuk menuntun generasi baru.
Ketiga, Kampanye Naratif – Gunakan cerita nyata (Ronzulli) dan cerita fiksi (novel) dalam materi edukasi untuk menyoroti risiko dan solusi secara seimbang.
Keempat, Evaluasi Dampak. Maksudnya lakukan survei tahunan pada karyawan perempuan tentang keseimbangan kerja‑keibuan, dan sesuaikan kebijakan berdasarkan data.
Melcy Making adalah penulis lepas dari Lembata-Nusa Tenggara Timur (NTT). Aktif menulis dibeberapa platfrom dengan fokus isu perempuan dan anak.
Editor: Nasruddin





















